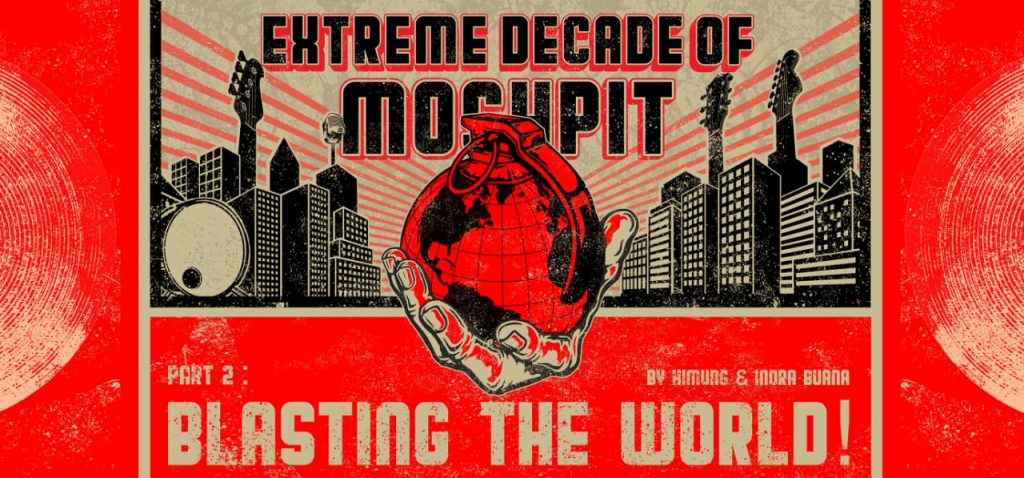Oleh : Kimun666
Tiga dekade setelah kelahiran kembali musik bawahtanah Indonesia, ranah ini berkembang pesat bahkan hingga ke titik yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tak hanya berbagai infrastruktur teknis yang berkaitan dengan ekosistem musik yang berkembang pesat di ranah ekonomi, sosial, dan budaya, transformasi gelombang musik ini juga sampai di ranah-ranah ideologi dan politik tanah air. Internasionalisasi musik ekstrim dengan berbagai program penetrasi global yang dilakukan oleh para musisi musik ekstrim terus dilakukan berhadapan dengan invasi musik internasional yang masuk ke Indonesia.
Di sisi lain, pergerakan globalitas ini juga melahirkan semangat terbarukan dalam melakukan penggalian nilai kearifan lokal yang kemudian secara abstraktif melahirkan ide-ide radikal mengenai glokalisasi dan konkritnya mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan musik hibrida yang unik dan otentik. Penggalian akar musik dan kesadaran akan identitas musik tanah air juga terjadi di ranah literasi kesejarahan yang tak melulu mengekspos nostalgia masa lampau yang tampak gemilang, namun jauh dari itu merancang masa depan yang lebih manifestatif, terstruktur, dan secara signifikan menjadi respon atas disrupsi budaya yang terjadi dengan begitu cepat.
Empat infrastruktur utama yang lahir sejak awal 1990an, yakni record label, gigs & festival, zine & media, serta crew secara siginifikan mengalami perubahan baik dalam teknik produksi, metode distribusi, pola konsumsi, dan semakin mencuatnya berbagai upaya konservasi yang dilakukan oleh para penggiatnya. Mengingat produksi rekaman merupakan bahan bakar utama bergeraknya musik dalam sisi apa pun, maka perubahan sistem analog menuju digital pada gilirannya merupakan faktor utama disrupsi ini dan dalam banyak hal mempengaruhi berbagai sistem lainnya. Digitalisasi sistem ini bersambut mesra dengan semakin merakyatnya internet sejak awal 2000an. Teknologi ini kemudian memicu lahirnya net label, blog, media sosial, platform digital distibusi musik, selain juga aplikasi teknologi terbaru di ranah seni pertunjukan dan festival. Hari ini, kita bisa menikmati konser secara virtual di kamar kita melalui handphone atau laptop, ruang-ruang yang dulu menjadi sangat sosial kemudian masuk merasuk di ranah-ranah kehidupan yang sangat personal.
Hal ini mengubah perilaku para penggemar musik ekstrim dari yang sangat eksklusif dan otentik sejak awal 1990an, menjadi kondisi yang lebih terbuka, inklusif, dan semakin sulit untuk teridentifikasi pada awal 2000an hingga kini. Jika pada 1990an para penggemar musik ekstrim sebutlah rock, punk, hardcore, metal, serta turunan-turunannya cenderung sangat setia terhadap musik yang mereka dengarkan dan bahkan merepresentasikan hasrat musik mereka secara politis melalui attitude dan fashion yang mencirikan musik yang ia dengarkan, sejak keterbukaan dan banjirnya musik identifikasi ini semakin mencair. Tentu saja ini perluasan pasar jika dilihat secara ekonomis, namun dalam banyak hal ada origin yang berubah dan harus ditelaah serta disikapi, tak hanya dalam seluruh seluk beluk ranah musik ekstrim, tetapi juga dalam keterhubungan ranah musik ini dalam lingkaran masyarajat yang jauh lebih besar.
Di sisi lain, teknologi internet yang sampai hingga ke laptop di pangkuan serta handphone di genggaman pada kelanjutannya menjadi sistem terstruktur yang membunuh konsep lama mengenai bawahtanah dengan segenap imajinasi “kegelapan”nya, menjadi ruang-ruang media yang terang tepat di depan wajah kita. Inilah aufklarung bentuk lain yang kemudian menjelmakan bawahtanah menjadi sosok lain. Tak ada lagi sistem tersembunyi di bawahtanah yang tak terlihat, tak terlacak, dan tak terpetakan. Kita bisa terkoneksi dengan musisi mana pun dari ujung dunia yang sebelumnya tak pernah kita ketahui saat musisi tersebut masuk ke dalam dunia terang internet. Para “pangeran kegelapan” kini tak lagi bersebunyi dalam gelap. Ia tercerahkan, tampil dalam limpahan cahaya yang penuh di layar-layar media, yang jika kita matikan laptop atau handphone kita, maka ia pun mati seketika. Konsep mengenai rockstar akhirnya berubah, seiring dengan sudut pandang audiens terhadap personifikasi “bintang-bintang yang jatuh” yang perlahan menjadi banal.
Perubahan ini tentu saja niscaya, seniscaya kita yang pada akhirnya harus segera merumuskan berbagai hal terjadi dalam dekade sebelumnya, membangun narasi tentang apa saja yang sudah dan masih kita miliki, dan pada akhirnya menjadikan narasi-narasi ini sebagai pedoman dalam membangun desain pergerakan musik pada masa yang akan datang agar tidak menjadi gegar saat terbentur perubahan jaman yang sangat cepat. Keniscayaan semakin siginifkan kala kemudian kita sampai di satu nilai kuantitas massa musik ini yang pada tahun 2008 saja sudah mencapai nilai 30.000 massa, hanya di Kota Bandung. Ranah musik ini berkembang, ia tak lagi teralienasi dan perlahan menjadi bagian penting yang ikut serta membangun wajah baru pergerakan anak-anak muda di kota-kota di Indonesia.
Perkembangan teknologi informasi yang sangat kuat akhirnya membuka keran eksposur ranah musik ini. Masyarakat dengan mudah menyerap beragam informasi mengenai musik ini dan semakin memahami potensi-potensi yang sudah dibangun oleh para penggiatnya. Di satu sisi ini tentu saja menjadi jalan keterpaduan dan keterbukaan yang merupakan metode utama dalam mengembangkan masyarakat yang integratif. Banyak lingkung masyakarat di luar ekosistem musik yang kemudian saling bersinggungan, terutama dari kalangan korporasi besar. Mereka merapat dan ikut ambil bagian dalam dinamika pembangunan ekosistem musikal, terutama yang berkaitan dengan mobilisasi massa besar, baik secara luring, mau pun secara daring.
Ini tentu saja menggembirakan karena suntikan energi dari korporat besar sedikit banyak memungkinkan para penggiat musik untuk bereksperimen berbagai kemungkinan kekaryaan yang sebelumnya tak bisa dilakukan. Namun di sisi lain, saat massa menjadi target utama yang dipentingkan, maka komodifikasi kemudian terulang lagi. Ranah musik ini tak lebih hanyalah menjadi objek dalam membagun imaji-imaji orang banyak mengenai gerak ringkah korporasi. Hal ini tentu saja seharusnya tidak perlu terjadi.
Yang banyak tidak disadari oleh para musisi saat berada dalam platform kerja sama dengan korporat besar adalah bargaining posisi yang seimbang. Dalam arti, korporasi memiliki banyak hal untuk membiayai produksi, sementara ranah musik memiliki ekosistem yang sudah lengkap, solid, dan kuat. Dalam kondisi keduanya memiliki keberimbangan potensi, maka komodifikasi akan terhindarkan, malah akan menciptakan standar-standar baru dalam hubungan antara musisi dan korporasi yang jauh lebih menguntungkan bagi ke dua pihak. Karena itulah, sebesar apa pun sebuah ranah musik sudah berkembang, maka pekerjaan rumah utama mereka adalah tetap memantapkan ekosistem yang menjadi ruang hidup mereka serta generasi-generasi selanjutnya.
Dan akhirnya, wacana mengenai regenerasi memang akhirnya menjadi narasi utama dalam perjalanan tiga puluh tahun musik ekstrim bawahtanah Indonesia. Berbagai skema dijalankan baik oleh para pionir mau pun oleh para musisi muda untuk terus menemukan posisinya masing-masing dalam dunia yang semakin kencang berputar dan terkadang menerbitkan kebingungan-kebingungan yang wajar dalam begitu cepatnya sebuah pergerakan. Orang kemudian menyebut itu sebagai gap. Sebetulnya bukan itu. Yang terjadi adalah bagaimana generasi satu dengan lainnya bisa menemukan pola bersenang-senang yang sama dan saling memahami bahwa Indonesia hanyalah sebuah ruang kecil jika dibandingkan indsustri musik metal global. Berbagi peran penguasaan industri negara sendiri oleh anak ibu pertiwi kemudian akan berkelindan dengan bagaimana para pionir mempergunakan seluruh pengalaman, koneksi, jaringan, dan jam terbangnya dalam membuka kemungkinan-kemungkinan baru dalam konsep musik metal hari ini—dan minimal tiga puluh tahun ke depan.
All hail extreme minded!
All hail 2020, all hail 2021!